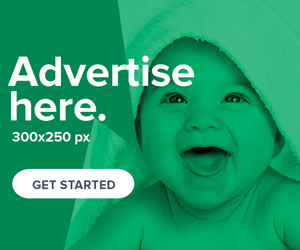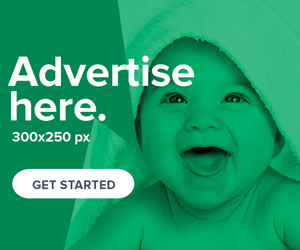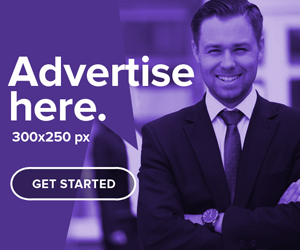Bogor Group - AKHIR-AKHIR ini publik disajikan drama politik yang tidak lucu berkaitan proses pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak di 171 wilayah pada Juni 2018. Banyak partai yang melakukan tarik ulur dukungan kepada bakal calon yang semakin menegaskan diktum politik lama bahwa yang pasti dalam politik ialah ketidakpastian itu sendiri. Pilkada Jawa Barat merupakan contoh sempurna. Golkar tiba-tiba mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur. PKS mendadak balik arah dan mengalihkan dukungannya dari Deddy Mizwar ke Mayjen (Purn) Sudrajat.
Dalam proses penentuan calon kepala daerah dan membangun koalisi dalam pilkada, partai-partai umumnya memakai tiga pertimbangan penting. Pertama, elektabilitas calon kepala daerah yang akan diusung. Inilah variabel penting yang sering menjadi dasar partai dalam memberikan rekomendasi. Partai sadar bahwa popularitas calon lebih menentukan hasil akhir pilkada ketimbang mesin partai.
Pilkada 2018 adalah 'semifinal' menuju Pilpres 2019 sebagai grand final kompetisi elektoral. Inilah yang menyebabkan politik zigzag lebih sering terjadi dalam dinamika pilkada kali ini. Hengkangnya PKS dalam koalisi pendukung Deddy Mizwar tak bisa dilepaskan dari desain koalisi 2019 yang ingin dipatenkan antara PKS, Gerindra, dan PAN. Twitwar awal tahun antara Deddy Mizwar dan Hidayat Nurwahid mengenai kontrak politik yang ditandatangani Deddy terkait komitmennya menyukseskan capres yang diusung Partai Demokrat merupakan bukti bahwa pilkada 2018 tak bisa dilepaskan aromanya dari pilpres 2019. Pertemuan khusus Prabowo Subianto, Shohibul Iman, dan Zulkifli Hasan menjadi pretext mundurnya PKS dalam barisan pendukung Deddy.
Jika faktor Pilpres 2019 dianggap penting dalam mendesain koalisi pilkada, apakah ada hubungan linear antara sukses elektoral di pilkada dengan pilpres? Data menunjukkan sejak rezim pilkada dimulai sejak 2005, tak ada korelasi antara hasil pilkada dengan pilpres maupun pemilu legislatif. Kemenangan calon dalam pilkada tak serta merta menjadi garansi sukses partai di pileg atau pilpres. Jawabannya sederhana, pemilih makin bersifat otonom. Selain itu, calon kepala daerah yang unggul umumnya juga diusung oleh banyak partai.
Meskipun tak ada hubungan linear, karena momentum pilkada hanya beberapa bulan sebelum pemilu serentak 2019, secara psikologis hasil pilkada mempengaruhi kesiapan dan kepercayaan diri partai-partai dan bakal capres yang akan berlaga nantinya. Hasil pilkada 2018 terutama di provinsi-provinsi dengan populasi gemuk seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan akan dilihat sebagai indikator sukses awal jelang hajatan 2019.
Tiga provinsi di Jawa yang akan menggelar pilkada di 2018 misalnya, menyumbang 47% dari total populasi pemilih di Indonesia. Lebih khusus lagi Jawa Barat yang selama ini menjadi barometer pemilu legislatif dan Jawa Timur yang menjadi barometer pilpres, tentu akan mendapat perhatian tersendiri dari kalangan elite dalam rangka meraih sukses di pemilu serentak 2019. Inilah pilkada dengan rasa nasional, dan partai-partai dan bakal capres akan memanaskan mesinnya dengan 'menunggangi' pilkada serentak 2018 ini.
Dengan tingkat kedekatan terhadap partai (party ID) yang rendah di Indonesia (survei Indikator Politik Indonesia terakhir hanya di kisaran 10%) dan keanggotaan partai (party membership) yang sangat minimalis, politik elektoral kita lebih dipengaruhi magnet elektoral calon yang diusung partai ketimbang partai. Akibatnya, dengan dalih elektabilitas kuat, partai sering memberi tiket kepada calon yang bukan berasal dari partai ketimbang kadernya sendiri. Koalisi dalam pilkada menjadi sangat cair dan nirideologis.
Kedua, kecukupan syarat teknis pencalonan kepala daerah juga menjadi pertimbangan krusial. Kita tahu, dalam UU terbaru, partai atau gabungan partai baru dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Banyak partai yang tak punya kemewahan mencalonkan tanpa koalisi dengan partai lain.
Akibatnya, banyak di antara mereka yang bermanuver dalam menjodohkan calon yang digadang-gadang dengan calon dari partai lain guna memenuhi ambang batas pencalonan yang tinggi. Jika partai pengusung lebih dari dua, sedangkan jatah posisi calon kepala daerah dan wakilnya terbatas, proses barter umum dilakukan untuk 'membeli' perahu atau uang mahar. Inilah awal dari kawin paksa politik yang sering menjadi penyebab pecah kongsi pasangan kepala daerah jika mereka terpilih.
Terakhir, faktor koalisi linear pilkada dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Inilah variabel baru dan aktual yang turut memengaruhi Pilkada serentak 2018. Sebelum 2018, faktor elektabilitas cenderung mendominasi pertimbangan partai dalam menentukan pilihan. Kini pertimbangan koalisi pilkada linear dengan koalisi pilpres jadi penting. Berhubung Pilkada 2018 akan diselenggarakan 9 bulan sebelum pilpres 2019, bahkan hanya 2 bulan sebelum proses nominasi capres via KPU, aroma pilpres sangat terasa dalam penentuan koalisi pilkada.
Dosen FISIP UIN Jakarta
Advertisement