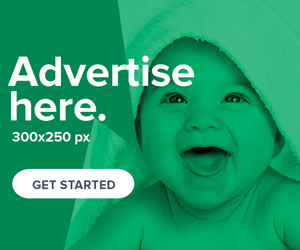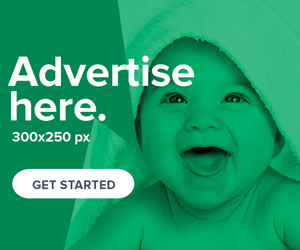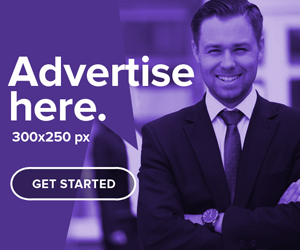BARU-BARU ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis kajian tentang beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang terpapar ajaran fundamentalisme. Fakta ini bukan isapan jempol, bukan fenomena baru. Ajaran fundamentalisme sudah menyusup ke sekolah-sekolah SMA, kampus sejak puluhan tahun yang lalu.
Dita Oepriharto, pelaku bom bunuh diri di Surabaya, misalnya, sejak di SMA ialah peserta aktif organisasi kerohanian Islam (rohis). Meskipun tidak semua organisasi pengaderan berbasis agama mengajarkan fundamentalisme, beberapa di antara mereka memiliki materi pengajaran keagamaan yang sangat tertutup dan ideologis. Bahkan, di kelompok ini terdapat materi rihlah dalam bentuk praktik latihan perang-perangan.
Yang menarik dari rilis BNPT ialah fakta dari mahasiswa eksakta yang paling banyak terlibat dalam organisasi fundamentalisme ini. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa eksakta lebih rentan terpapar gerakan fundamentalisme? Padahal, dalam proses seleksi perguruan tinggi, jurusan eksakta sering dianggap sebagai tempat bagi anak-anak pilihan di sekolah asalnya. Di sinilah paradoksnya. Kecerdasan IQ (intelligence quality) tidak berbanding lurus dalam menyeleksi ajaran ekstrem. Sebaliknya, mereka justru menjadi kelompok paling rentan, mudah disusupi ajaran ekstrem.
Salah satu daya tarik ajaran fundamentalisme bagi siswa/mahasiswa ialah gagasan 'kebangkitan Islam di dunia modern'. Suatu idiom yang tak pernah ditemukan di dalam ajaran-ajaran pendidikan pesantren maupun pendidikan agama konvensional. Gagasan ini sebenarnya merupakan proliferasi dari pergulatan pemikiran Islam di Timur Tengah yang dirintis sejak zaman Ibn Taimiyah (abad ke-13). Lalu, berkembang menjadi gerakan Wahabiyah (1703-1878) dan menjadi alat propaganda paling berpengaruh sejak Ikhwanul Muslimin di Mesir di awal abad ke-20.
Tema Kebangkitan Islam ialah gagasan yang hendak menegaskan autentisitas Islam di tengah kepungan Westernisasi. Islam sebagai jalan hidup menyeluruh yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam yang memiliki tujuan untuk mengubah sistem dunia yang dianggap sekuler dan produk orang-orang kafir. Distingsi 'Islam-kafir' ditegaskan dalam doktrin ini. Ia menjadi praktik politik di masa Sayyid Qutb (1906-1966).
Doktrin-doktrin Islam disampaikan sebagai sumber kepastian, rujukan paling autentik meniti jalan hidup yang benar. Islam seperti ini disuguhkan dalam nalar ideologis dan mistis. Daya persuasi yang digarap kelompok-kelompok ideologis ini semakin bergema di saat pendidikan sekolah/kampus tidak mengajarkan dan menjawab persoalan manusia yang bertolak dari pertanyaan why to live.
Pertanyaan eksistensial yang mewacanakan tujuan hidup manusia dan tugas ilahiah yang harus diembannya. Sayangnya, sekolah/kampus lebih menekankan pengetahuan teknis dan keterampilan, lebih condong menjawab how to live.
Sebagaimana kita ketahui, mahasiswa fakultas eksakta banyak disibukkan dengan praktikum, waktunya habis di laboratorium jika dibandingkan dengan jurusan sosial. Mereka tidak memiliki waktu banyak untuk bersosialisasi, bertatap muka dengan mahasiswa lain, atau masyarakat di sekitar yang memiliki latar belakang yang beragam.
Bahkan, mahasiswa ilmu sosial terbiasa dengan pemikiran yang beragam, memiliki pengetahuan bahwa persoalan sosial kemanusiaan tidak hitam-putih. Ia dipenuhi dengan ambiguitas, ambivalensi, dan bisa jadi paradoks.
Sebaliknya, wacana kebangkitan Islam membangun narasi tentang persoalan aktual secara hitam putih 'kita-mereka', 'Islam-kafir' secara provokatif. Pada satu sisi, ia menggambarkan dekadensi moral akibat penguasaan peradaban oleh kaum kafir. Di sisi lain mengkritik kemunduran umat Islam karena dianggap sekadar menjadi pengikut peradaban.
Misalnya Sayyid Qutb menggambarkan situasi umat Islam seperti ini sebagai skizofrenia. Mengutip kata-kata Sayyid Qutb, "Ketika kesadaran manusia diperintah hukum tertentu, tetapi kehidupan dan aktivitas aktualnya diperintah oleh hukum yang lain, dan ketika kedua hukum itu timbul dari konsepsi yang berbeda, yang satu adalah imajinasi manusia dan yang lain adalah dari inspirasi Tuhan, individu itu pastilah menderita semacam skizofrenia (Qutb, 2007)."
Sayyid Qutb salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, mengajak revolusi untuk mendirikan negara Islam demi menumbangkan watak skizofrenia ini. Gagasannya lalu dijadikan alat propaganda menjadi referensi dalam materi pelatihan gerakan-gerakan keagamaan.
Ironisnya, di Indonesia model gerakan ini sudah dipraktikkan sejak dekade 1980-an. Mereka masuk ke kampus dan sekolah-sekolah setingkat SMU, direproduksi dari tahun ke tahun tanpa sikap kritis. Padahal, gagasan ini dipenuhi dengan simplikasi dan reduksi.
Tidak ada resep yang lebih manjur dalam upaya mengatasi gerakan fundamentalisme kecuali melakukan upaya dekonstruksi. Skizofrenia sebagaimana disiratkan Qutb bisa jadi telah berlangsung. Namun, hal ini terjadi karena pendidikan agama nyaris berdiri otonom tanpa disandingkan dan dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Bahkan kerap kali gagasan di antara keduanya saling bertabrakan. Menjadi umat Islam adalah satu hal, menjadi warganegara adalah hal lain. Selama ini tidak pernah ada evaluasi atas berkembangnya konsep-kafir yang muncul di materi-materi pendidikan keagamaan.
Kita baru menyadarinya sebagai persoalan ketika konsep-konsep ini berembus ke dalam wacana politik, dijadikan modal bagi kontestan pilkada untuk menihilkan pihak lain. Padahal, tidak ada yang menyangkal bahwa relasi antara doktrin keagamaan (Islam) dan politik bukan sesuatu yang ahistoris.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tinjauan terhadap semua materi pendidikan agama dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Riset PPIM-UIN Jakarta 2018 semakin menegaskan peran pendidikan agama yang mendorong sekat antarsiswa yang berbeda agama. Buku-buku pelajaran agama harus ditulis ulang untuk memastikan konten materi keagamaan yang lebih ramah terhadap keragaman, merekatkan persaudaraan, dan menonjolkan aspek penghormatan terhadap HAM.
Diskursus Kebangkitan Islam yang diperhadapkan secara asimetris dengan Peradaban Barat/kafir harus didekonstruksi dengan Islam rahmatan lilalamin. Konsep kafir perlu dicarikan tafsiran yang lebih progresif agar konsep-konsep ini tidak berlawanan dengan komitmen umat Islam sendiri di Indonesia yang menyepakati Pancasila sebagai kalimatusawa (kesepakatan bersama) dalam membangun kehidupan berbangsa.
Nilai kebangsaan harus menjadi bagian iman umat beragama. Nilai-nilai penghormatan terhadap keragaman, pluralisme, harus ditanamkan sejak dini di dalam pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, dalam upaya meretas intoleransi, guru-guru agama, penulis materi pendidikan agama, perlu berkiblat pada gagasan Islam rahmatan lilalamin yang meletakkan moral/doktrin agama dalam satu tarikan napas dengan moral Pancasila. Keduanya tidak boleh saling menafikan.
Penulis: Muhammad Nurkhoiron
Komisioner Komnas HAM 2012-2017,
Ketua Yayasan Desantara
Advertisement